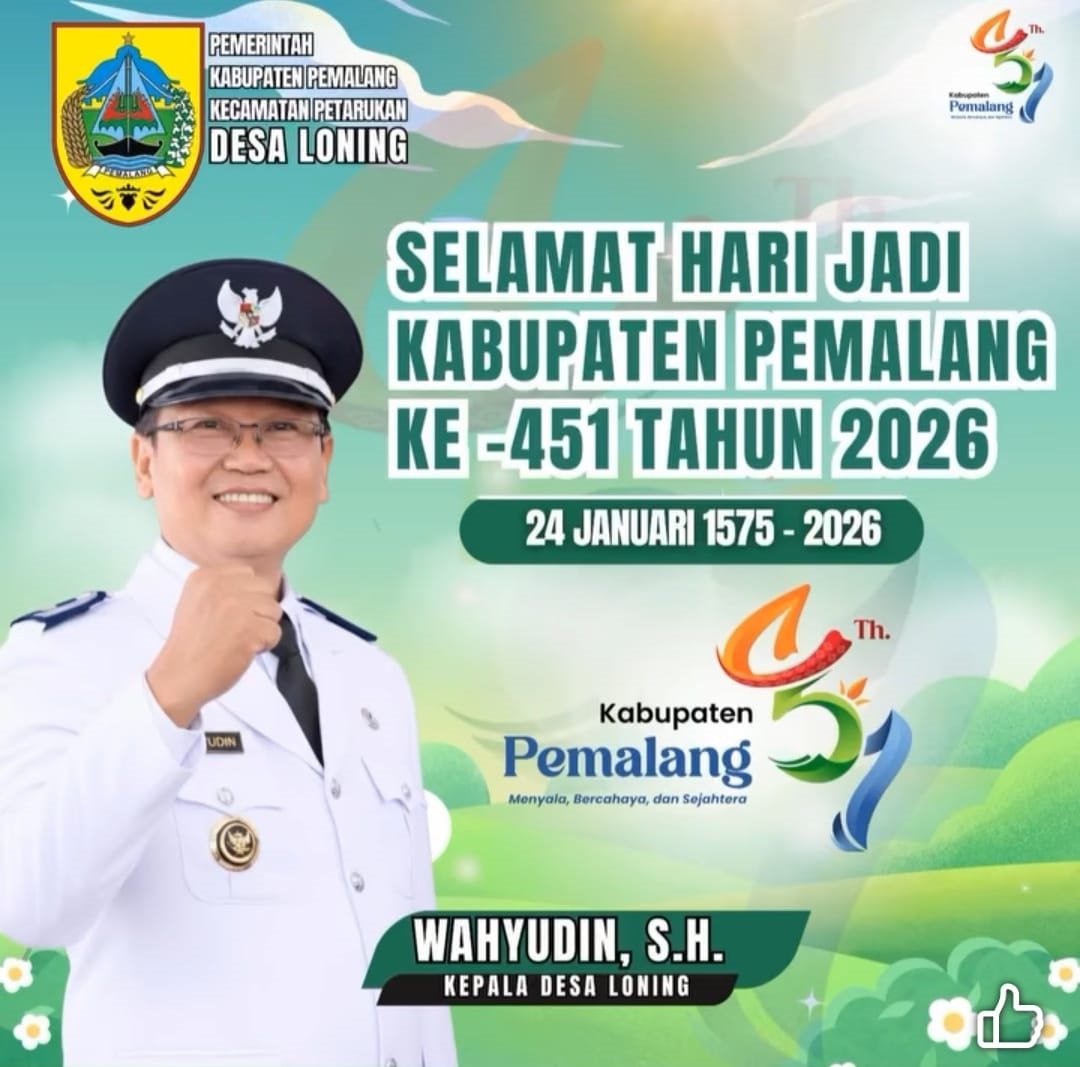Harianpemalang.id, Pemalang – Isu tentang larangan kepala desa untuk terlibat dalam politik praktis kembali memanas di tengah dinamika demokrasi Indonesia. Aturan yang mengikat jabatan ini, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memicu perdebatan sengit antara upaya menjaga netralitas pemerintahan desa dan jaminan hak politik konstitusional warga negara. Di Kabupaten Pemalang, suara-suara dari akar rumput mulai lantang menyuarakan keresahan atas pembatasan ini.
Sarwono, Kepala Desa Kecepit, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menjadi salah satu figur yang secara terbuka menyuarakan keberatannya. Ditemui pada Rabu, 16 Juli 2025, Sarwono mengungkapkan bahwa larangan tersebut terasa membatasi ruang gerak kepala desa sebagai warga negara yang juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
“Kami ini dipilih langsung oleh rakyat, tapi hak kami untuk menjadi bagian dari kepengurusan partai politik justru dibatasi,” ujar Sarwono dengan nada prihatin. “Padahal, sebagai kepala desa, kami bersentuhan langsung dengan masyarakat, memahami aspirasi mereka, dan seringkali memiliki gagasan yang relevan untuk pembangunan di tingkat yang lebih luas.”
Larangan kepala desa terlibat dalam kepengurusan partai politik didasari oleh argumen utama mengenai perlunya menjaga netralitas birokrasi desa. Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan kepala desa dalam partai politik dapat memicu politisasi anggaran desa dan potensi konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan publik dan pembangunan desa yang objektif. Tujuannya adalah agar kepala desa dapat melayani seluruh warganya tanpa tendensi politik tertentu, serta fokus pada tugas-tugas administratif dan pembangunan desa.
Namun, di sisi lain, muncul argumen kontra yang mempertanyakan keadilan dan kesetaraan perlakuan hukum. Banyak pihak, termasuk para kepala desa sendiri, merasa bahwa pembatasan ini diskriminatif. Mereka membandingkan posisi kepala desa dengan pejabat publik lainnya, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau bahkan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang notabene diperbolehkan, bahkan didorong, untuk aktif dalam kepengurusan partai politik.
“Mengapa anggota DPR atau bahkan bupati/wali kota boleh menjadi pengurus partai, sementara kami yang juga hasil pemilihan langsung tidak?” tanya Sarwono. “Ini seperti ada standar ganda dalam penegakan hak politik.”
Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 dan 28D, secara jelas menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, termasuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Para kritikus larangan ini berpendapat bahwa pembatasan total terhadap kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik berpotensi melanggar prinsip dasar ini.
Keresahan yang disuarakan Kepala Desa Sarwono bukan tanpa dasar. Dalam beberapa studi hukum, seperti yang disampaikan oleh Wahyudin, S.H., Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum dari Universitas Pancasila Sakti Tegal yang juga Kepala Desa Loning, Kecamatan Petarukan. Dia mengatakan : larangan total tanpa adanya mekanisme alternatif dapat dianggap bertentangan dengan asas proporsionalitas dan nondiskriminasi. Wahyudin mengusulkan adanya solusi tengah, seperti implementasi mekanisme cuti politik.
Dengan skema cuti politik, seorang kepala desa dapat mengambil cuti dari jabatannya selama periode tertentu jika ia memutuskan untuk aktif dalam kepengurusan partai politik atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum di tingkat yang lebih tinggi. Setelah masa cuti selesai atau jika ia tidak terpilih, ia dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Mekanisme ini diharapkan dapat menjaga netralitas pemerintahan desa sambil tetap menghormati hak politik individu kepala desa.
“Jika tujuannya adalah menjaga netralitas, maka harus ada mekanisme yang adil. Mengapa tidak diterapkan cuti politik seperti ASN atau pejabat lain?” usul Sarwono. “Dengan begitu, hak kami untuk berpartisipasi diakomodasi, dan netralitas desa tetap terjaga.”
Polemik kepala desa dalam khasanah politik praktis ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam sistem demokrasi. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pelayanan publik di tingkat desa berjalan objektif dan bebas dari intervensi politik partisan. Di sisi lain, ada tuntutan kuat dari para kepala desa untuk diberikan perlakuan yang setara dan adil terkait hak politik konstitusional mereka.
Perdebatan ini diharapkan dapat memicu dialog lebih lanjut antara pemerintah, DPR, dan para kepala desa untuk menemukan solusi terbaik. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang tidak hanya menjamin netralitas pemerintahan desa, tetapi juga menghormati hak-hak dasar warga negara, termasuk mereka yang mengemban amanah sebagai pemimpin di garda terdepan pembangunan bangsa. Akankah suara dari Kepala Desa Kecepit ini menggema hingga ke Senayan dan memicu perubahan kebijakan? Waktu yang akan menjawabnya.( Joko Longkeyang).